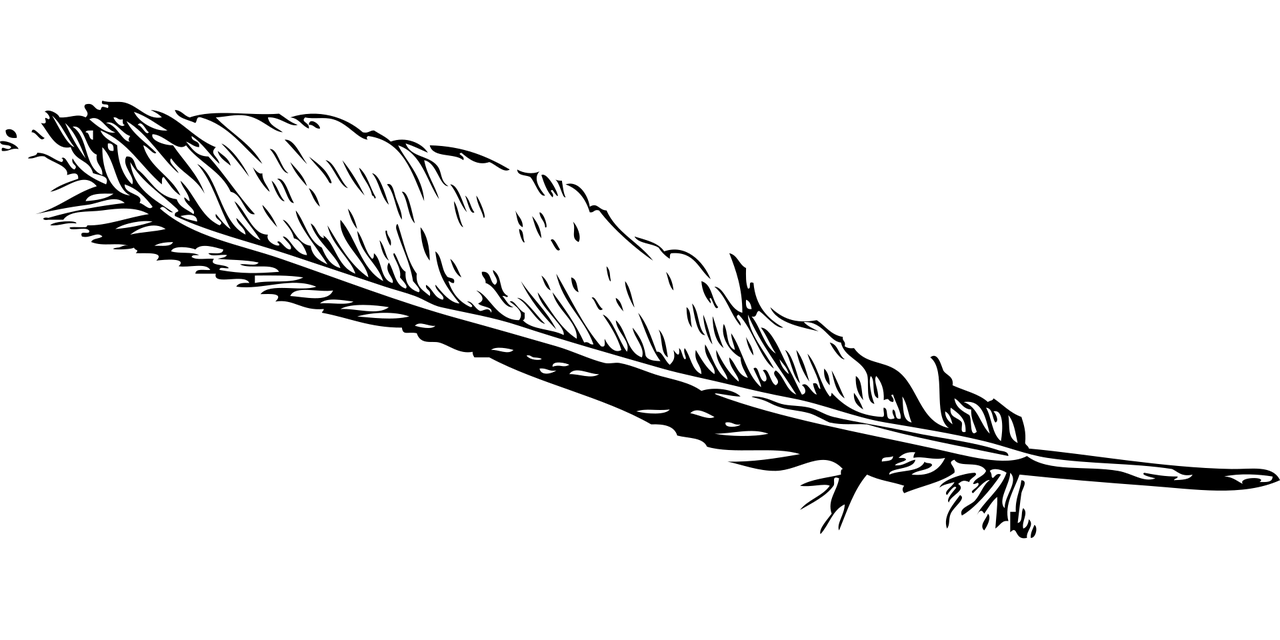Sejak pindah ke rumah baru di sebuah desa tepi hutan kecil, Meysha selalu memandang pohon jati besar di belakang rumah seperti melihat sesuatu yang memanggilnya. Pohon itu tinggi, rimbun, dengan cabang kuat yang seakan dibuat untuk dipanjat.
Melihat anaknya betah bermain di sana, ayah akhirnya membangun sebuah rumah pohon sederhana. Tidak besar, hanya cukup untuk satu anak duduk sambil membaca, tapi cukup kokoh untuk menahan tubuh Meysha yang kurus dan penuh rasa ingin tahu.
Rumah pohon itu langsung menjadi dunia kecilnya—tempat ia menggambar, bercerita pada boneka, atau sekadar duduk menatap langit sore.
—
Suatu minggu yang terik, Meysha tiba-tiba mendapat ide.
“Yah, boleh nggak kalau malam ini Meysha tidur di rumah pohon?”
Ayah terdiam sejenak. “Tidur? Sendiri?”
Meysha mengangguk penuh harapan.
Akhirnya ayah mengizinkan, meski wajahnya tampak ragu. “Tapi kalau dingin atau takut, langsung turun ke rumah, ya? Jangan memaksakan diri.”
Meysha mengangguk. Malam itu, dengan membawa selimut tipis, senter, dan buku cerita, ia naik ke rumah pohon. Angin malam semilir, membawa wangi tanah dan daun kering. Rumah pohon bergoyang pelan seperti buaian besar.
Awalnya Meysha tenang. Ia membaca, berbaring, mencoba tidur.
Hingga tiba-tiba ada ketukan perlahan dari sisi luar dinding.
Tok… tok… tok…
Meysha terbangun. Ketukannya halus, seperti anak kecil mengetuk dengan kuku.
Ia menahan napas. “Ayah?”
Tidak ada jawaban.
Ia menyorotkan senter ke jendela… dan hampir saja terloncat.
Di luar, di cabang pohon, duduk seorang anak perempuan. Umurnya mungkin sebaya. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya pucat diterpa sinar bulan. Kakinya menggantung, dan ia menatap Meysha tanpa kedip.
Meysha terdorong mundur. “K-kamu siapa?”
Anak itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak membuatnya terlihat hidup. “Namaku Pina.”
Meysha menelan ludah. “Kamu ngapain di sini?”
“Aku lihat lampu rumah pohonmu nyala. Aku mau main.”
Ada hal ganjil. Pina… tidak naik dari tangga. Ia duduk di luar, di cabang pohon yang bahkan tidak disentuh kakinya.
Namun rasa takut Meysha kalah oleh rasa penasaran.
“Kamu tinggal di mana?”
Pina menunjuk ke arah hutan kecil di belakang rumah. “Dulu… di sana.”
“Dulu?” ulang Meysha pelan.
Pina tidak menjawab. Tatapannya menerawang, seperti mengingat sesuatu yang jauh. Lalu ia bertanya pelan, “Boleh aku masuk?”
Meysha ragu. “Tangga ada di sebelah sana.”
Pina tersenyum, tetapi kali ini senyumnya terasa aneh. “Aku nggak bisa lewat tangga.”
Sebelum Meysha bertanya lebih jauh, angin kencang berhembus, membuat daun-daun jati bergetar keras. Pina memandang sekeliling, tampak gelisah.
“Aku nggak boleh lama-lama di sini,” katanya cepat. “Aku cuma… kangen.”
“Kangen apa?”
“Kangen punya teman.”
Mata Pina berkaca-kaca, dan tiba-tiba tubuhnya memudar seperti kabut. Dalam sekejap, ia hilang. Yang tersisa hanya suara dedaunan yang kembali tenang.
Meysha menjerit kecil dan langsung turun, berlari ke rumah.
—
Keesokan paginya, sambil sarapan, Meysha menceritakan semuanya pada ayah. Ayah menatapnya lama, wajahnya tegang seperti menyembunyikan sesuatu yang telah lama ia tahu.
“Nama anak itu siapa?” tanya ayah pelan.
“Pina.”
Ayah langsung menutup mulutnya, seperti tidak percaya.
“Yah?” Meysha khawatir.
Ayah menarik napas dalam. “Rumah ini… bekas ditinggali keluarga lain sebelum kita. Mereka punya anak perempuan bernama Pina.”
Meysha membeku.
“Dia meninggal tiga bulan sebelum kita pindah,” lanjut ayah lirih. “Tapi bukan karena jatuh dari rumah pohon. Dia tenggelam di sungai kecil di belakang hutan waktu hujan besar.”
Ayah menatap luar jendela menuju pohon jati. “Sejak itu… ada yang bilang Pina suka kembali ke tempat ia sering bermain dulu.”
Meysha merinding. Tiga bulan. Masih baru.
“Tapi Yah,” suara Meysha hampir tak terdengar, “dia bilang kangen punya teman.”
Ayah mengusap kepala Meysha lembut. “Jangan main malam-malam lagi di sana, ya?”
—
Meysha tidak kembali tidur di rumah pohon. Tapi ia sering naik ke sana saat sore. Duduk sambil mengayun kaki. Membaca buku. Menggambar.
Sesekali angin sore bertiup membawa suara samar, nyaris seperti bisikan seorang anak.
“Meysha… terima kasih ya.”
Ia tidak pernah melihat Pina lagi, tapi ia tak pernah lupa malam itu.
Sebab beberapa teman datang tanpa tubuh, tapi meninggalkan kenangan yang hangat.
Kisah Horror, “Teman Kecil di Pohon”