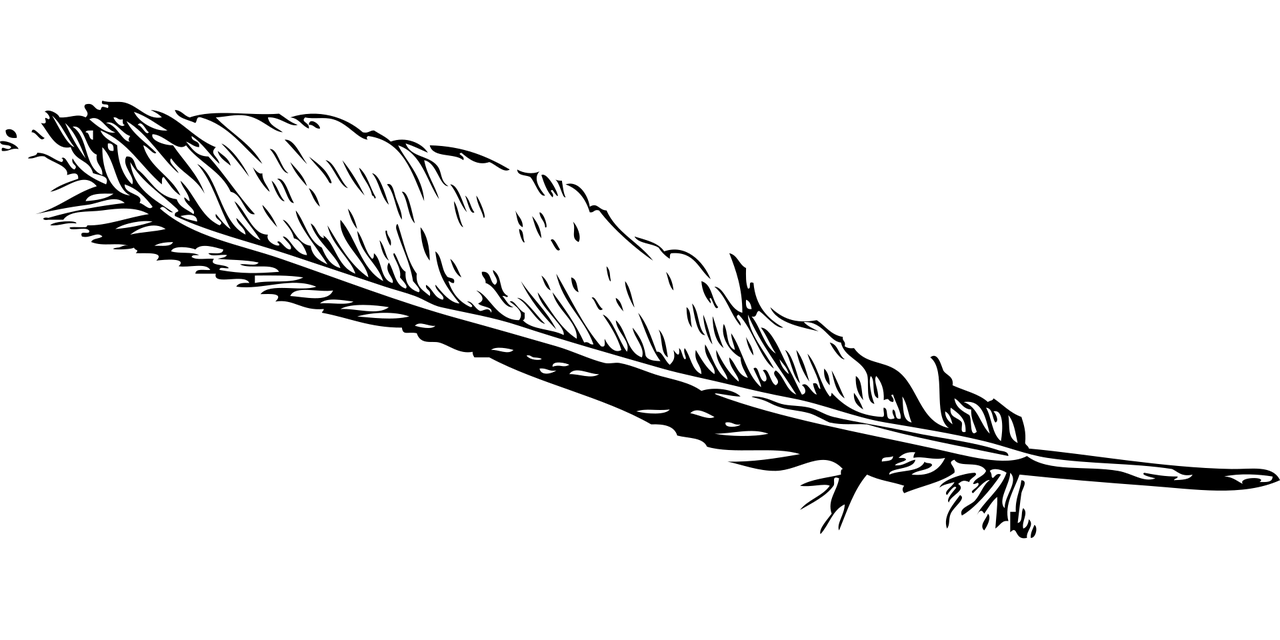Hujan turun sejak senja, memukul genting dan jendela kamar Aruna dengan irama yang biasanya menenangkan. Malam itu dingin, tapi udaranya lembut—cukup membuatnya cepat terlelap setelah hari panjang di sekolah.
Namun ketenangan itu terputus mendadak.
Di tengah malam, Aruna tersentak bangun. Dadanya berat. Napasnya pendek-pendek, seperti ada sesuatu yang menekan paru-parunya dari dalam. Ia mencoba berguling, tapi tubuhnya terasa kaku.
Rasanya seperti dicekik udara.
“Kenapa…?” bisiknya sambil terisak.
Ia meraih selimut, berniat mendorongnya agar bisa bernapas lebih lega. Tapi ketika ia menarik kain itu—
ada sesuatu yang mencengkeram lehernya.
Dingin.
Kaku.
Pucat.
Aruna membeku. Tangan-tangan itu melingkar erat, seolah ingin menguras habis udara dari tubuhnya. Ujung jari kurusnya menekan kulit leher Aruna, meninggalkan rasa dingin menusuk sampai ke tulang.
Ia ingin berteriak. Tak bisa. Hanya suara serak tercekik yang keluar.
Aruna meraih tangan itu, mencoba melepaskannya—tapi semakin ia menolak, cengkeramannya semakin kuat. Tubuhnya bergetar hebat, matanya berair, kepalanya berputar. Suara hujan di luar terdengar seperti jeritan.
Dan saat Aruna merasa detik berikutnya akan menjadi detik terakhirnya—
tangan itu hilang.
Begitu saja. Menguap dari lehernya. Napasnya mengalir kembali, keras dan berantakan. Ia meraba lehernya dengan gemetar, dan merasakan bekas-bekas pucat mirip sidik jari. Seperti tanda kecil yang tidak ingin pergi.
Ia menyalakan lampu. Cahaya kuning menerangi kamar yang tampak normal. Tidak ada siapa pun. Tidak ada tanda-tanda… apa pun.
Tapi dingin itu masih menempel.
—
Keesokan paginya, Aruna bercerita kepada neneknya yang tinggal tepat di rumah sebelah. Ia memperlihatkan bekas pucat di lehernya. Nenek menatapnya lama—begitu lama hingga Aruna merasa ada sesuatu yang disembunyikan.
Akhirnya, nenek bicara.
“Dulu, sebelum kamu tinggal di sini… kamar itu pernah ada kebakaran kecil,” ujar nenek lirih.
Aruna membungkam napasnya.
“Api berasal dari korsleting lampu meja. Kebakaran tidak besar, tapi asapnya memenuhi ruangan dengan cepat. Penghuni kamar saat itu—seorang gadis sebaya kamu—bangun terlambat. Ia batuk keras, tidak bisa melihat apa pun karena asap.”
Nenek meremas jemarinya sendiri, suaranya bergetar.
“Dia panik. Menutup wajahnya. Memegangi lehernya sendiri karena tenggorokannya sakit tercekik asap. Waktu ditemukan, tubuhnya sudah pucat sekali. Tangan-tangannya… masih mencengkeram lehernya sendiri, seolah mencari udara yang tidak ada.”
Aruna merasakan dingin merayap dari punggung sampai tengkuk.
“Kenapa dia… mencengkeram aku tadi malam?” tanya Aruna pelan.
“Nenek tidak yakin,” jawab nenek. “Tapi arwah yang tidak pergi dengan tenang sering mengulang momen terakhir sebelum mereka mati. Dan kamu… tidur di tempat yang sama, dengan lampu yang sama padamnya, pada hujan malam yang sama.”
Aruna terdiam, bibirnya bergetar.
“Lalu… kenapa dia melepas aku?”
Nenek menatapnya dengan mata sayu namun hangat.
“Karena akhirnya dia sadar kau bukan dirinya.”
—
Sejak malam itu, Aruna tidak pernah mematikan lampu saat tidur. Tidak pernah membiarkan hujan malam menjadi pengantar mimpi. Dan tidak pernah, sekalipun, berani tidur sendirian.
Karena kadang, ketika hujan turun tipis, ia masih merasakan hembusan dingin di lehernya—seolah tangan pucat itu masih mencoba mengingat bagaimana rasanya mencari napas untuk terakhir kalinya.
Kisah Horror, “Cengkraman di tengah Hujan”